Pemerintah sengaja mewariskan beban jebakan hutang infrastruktur bagi rezim berikutnya
Pemerintah Indonesia, melalui Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menawarkan 28 proyek di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) II Belt and Road Initiative yang digelar di Beijing April 2019. Tak tanggung-tanggung, nilai proyek yang ditawarkan bernilai US$91,1 miliar atau setara dengan Rp1.296 triliun.
Analis ekonomi politik Kusfiardi menilai, penawaran proyek tersebut masih sangat jauh dari pengetahuan masyarakat. Terutama dampaknya terhadap kepentingan nasional seperti penguasaan sumber-sumber ekonomi, maupun penguasaan objek vital seperti pelabuhan dan bandara.
Mengutip data-data Bank Indonesia, Kusfiardi merinci utang Indonesia ke China meroket hingga 74% pada 2015. Pada 2014, total utang RI ke China adalah US$7,87 miliar. Angkanya melesat menjadi US$13,6 miliar pada 2015. Pada 2016, utang ke China menjadi US$15,1 miliar di 2016 dan US$16 miliar per Januari 2018.
"Pemerintah sepertinya abai dengan besarnya beban utang yang ada saat ini, membuat keseimbangan primer APBN mengalami defisit. Pemerintah menggunakan utang baru untuk membayar utang lama yang jatuh tempo. Apakah pemerintah sengaja mewariskan beban bagi rezim berikutnya dengan masalah jebakan utang infrastruktur?" jelas Kusfiardi, Rabu (10/4/2019).
Sebagai perbandingan, CO Founder FINE Institute ini memaparkan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, meninjau ulang dan membatalkan sejumlah proyek untuk mengurangi beban utang. Bahkan Pemerintahan Malaysia akan menegosiasikan ulang proyek Jalur Sutra Maritim China yang disebutnya tidak menguntungkan Malaysia.
Malaysia merupakan salah satu negara yang mendapatkan investasi terbesar dari proyek BRI. Negeri jiran menempati posisi strategis untuk untuk konektivitas perdagangan dari Asia hingga Afrika. Dana sebesar US$34,2 miliar diperuntukkan China membangun infrastruktur BRI di Malaysia.
"Dalam penilaian Mahathir, perjanjian pinjaman China tidak menguntungkan. Selain tidak mempekerjakan warga lokal, China juga tidak berbagi teknologi dengan Malaysia," sambungnya.
Tak hanya Malaysia, Kusfiardi menyebut Filipina juga tengah meninjau ulang semua kontrak pemerintah, termasuk pinjaman dari China. Fokus yang ingin ditekankan oleh otoritas Filipina ialah perjanjian konsesi dan kontrak pinjaman dengan ketentuan yang tidak menguntungkan Filipina yang mencakup US$12 miliar hingga US$24 miliar dengan beberapa proyek untuk menghapus ketentuan yang tidak menguntungkan bagi Filipina.
"Kekhawatiran terbesarnya adalah, China dapat merebut aset Filipina jika tidak dapat membayar kembali pinjaman tersebut," terang Kusfiardi.
Dalam skala yang lebih luas, pemerintah Pakistan, Nepal dan Myanmar juga melakukan pembatalan kontrak proyek infrastruktur dengan China. Merujuk pada Standard & Poor’s, proyek-proyek infrastruktur di bawah kebijakan Belt and Road Beijing itu, adalah utang konsesi jangka panjang. Konsesi utang itu akan memberikan hak kepada perusahaan China untuk mengoperasikan fasilitas itu selama 20-30 tahun.
Bahkan Direktur IMF Christine Lagarde mengemukakan, kekhawatiran akan masalah utang ini dan meminta agar ada transparansi yang lebih besar.
"Lagarde juga mengatakan, utang bukan sesuatu yang gratis. Utang ini adalah sesuatu yang harus dibayar oleh semua pihak. Bentuk yang harus dibayar itu bisa sangat memengaruhi kondisi perekonomian nasional sebagai bangsa yang berdaulat," jelas Kusfiardi. (Alf)
Penulis : Alfian Risfil
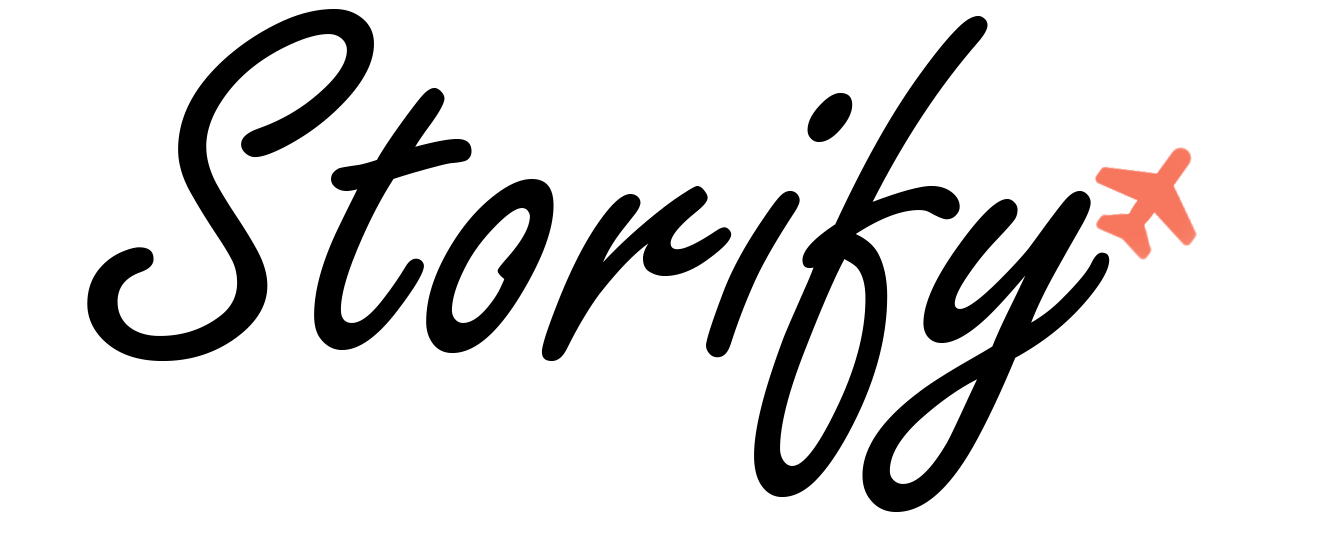









COMMENTS