Kekuasaan modal memiliki kekuatan yang tak kalah dashyat, bahkan mungkin lebih dashyat daripada kekuasaan negara itu sendiri
Dalam perspektif Marxian, media massa berpotensi menyebarkan ideologi dominan. Ideologi dominan biasanya disebarkan oleh orde yang berkuasa dalam rangka mengekalkan kekuasaannya.
Dalam rangka mengekalkan kekuasaan tersebut, kelompok yang dominan melalui media cenderung menyuarakan kepentingannya dan berusaha agar kelas lain turut serta berpartisipasi dengan sukarela, atau tanpa mereka sadari dan itulah yang disebut sebagai “hegemoni”.
Di Indonesia sendiri pada masa Orde Baru, Media Massa mendapat kontrol yang begitu ketat dari penguasa dan menjadi corong untuk melanggengkan kekuasaannya dengan melakukan Hegemoni.
Seperti pemutaran secara berkala Film peristiwa G 30 S/PKI yang penuh rekayasa dan pembelokan sejarah dan sampai saat ini masih menyisakan pengaruh bagi sebagian masyarakat di Indonesia sehingga sampai sekarang kita mengenal ada organisasi yang menamakan dirinya front anti komunis yang dibentuk secara sukarela oleh masyarakat itu sendiri.
Ketika memasuki Era reformasi di mana Media Massa menikmati kebebasannya dan tidak lagi menjadi corong bagi penguasa, akan tetapi tidak berarti dengan serta merta media massa, terutama Televisi, bebas dari kontrol pihak tertentu ibarat keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa begitulah kira-kira penggambaran dari kondisi media massa saat ini.
Meski tidak lagi menjadi corong penguasa akan tetapi media massa tidak pernah lepas dari intervensi sang pemilik modal yang dikuasai oleh segelintir orang yang nota bene memiliki beragam kepentingan taruhlah seperti kepentingan ekonomi, politik dan ideologi tertentu.
Konglomerasi Media Di Indonesia
Ketika berbicara tentang media massa, dalam hal ini media penyiaran Televisi, maka kita akan dapat menarik garis besar kepemilikan yang berpusat pada segelintir orang. Dalam hal ini Trans7 dan Trans TV berada pada payung bisnis yang sama yakni Trans Corp yang dikuasai oleh Chairul Tanjung, Global TV, RCTI dan TPI bergabung dalam Group MNC dan bertindak selaku pemilik di Indonesia adalah Hary Tanoesoedibyo.
TV One dan ANTV bernaung di bawah bendera Bakrie Group dengan Boss utama Abu Rizal bakrie, SCTV yang sebahagian besar sahamnya dimiliki oleh Eddy Sariatmadja, dan yang terakhir Metro TV dengan pimpinannya yang termasyhur karena wajahnya sering ditampilkan oleh TV yang dimilikinya sendiri.
Singkat kata, nama-nama pemilik media yang disebutkan di atas tadi merupakan orang-orang yang membangun kerajaan bisnisnya dengan berupaya dekat dengan kekuasaan dan beberapa di antara ada yang duduk sebagai orang penting di pemerintahan serta ada pula yang merupakan tokoh penting pada salah satu partai yang sekian lama berkuasa di republik Ini (baca Golkar).
Tidak menutup kemungkinan mereka membangun Media untuk memuluskan kepentingannya dalam bidang politik dan penyebaran ideologi tertentu, melaui media. Hal itu dapat dilihat dari wajah media yang mereka bentuk, di mana saat ini banyak media yang mengawal kepentingan penguasa seperti yang baru baru ini terlihat bagaiman televisi ramai-ramai menyiarkan Rapimnas Partai Golkar padahal di sisi lain masih banyak agenda-agenda penting lainnya yang harus diketahui oleh Publik
Padahal salah satu hak yang harus didapat masyarakat dari media adalah mereka mendapatkan Diversity Informasi atau keanekaragaman informasi. Tentu saja Konglomerasi media ini sangat tidak sehat dalam iklim berdemokrasi dan perpolitikan bangsa ini mengingat pengaruh media yang begitu kuat terhadap kognitif khalayak.
Jika mengacu pada Jurgen habermas menyatakan media massa sesungguhnya adalah sebuah Public Sphere yang semestinya dijaga dari berbagai pengaruh dan kepentingan. Dalam arti, media selayaknya menjadi
The Market Places Of Ideas, tempat penawaran berbagai gagasan sebagaimana setiap konsep pasar, yang mana hanya ide terbaik sajalah yang pantas dijual dan ditawarkan. Salah satu bentuk konglomerasi media adalah terpusatnya kepemilikan media massa oleh para penguasa modal. Fenomena itu dinilai berimplikasi terhadap obyektivitas media dalam menyampaikan muatan-muatannya.
Konglomerasi media menjadikan orientasi media cenderung ke arah industri, bukan fungsi jurnalismenya. Akibatnya, media lebih mengutamakan tayangan informasi-informasi yang menarik saja ketimbang yang penting.
Toriq memaparkan para pihak yang mempunyai kuasa untuk menghegemoni media, yaitu negara, pengusaha, media sendiri, serta civil society.
Menurutnya kemenangan kapitalisme menjadi konsekuensi logis ter-hegemoninya media oleh modal. Hegemoni modal seakan bertumpang tindih dengan kepentingan politik. Ini karena para pemilik media besar di Indonesia, selain mempunyai kekuatan modal, sekaligus menempati posisi strategis politik Nasional.
Di sisi lain, Djadjat berpendapat, hegemoni adalah godaan yang harus dihindari, namun tidak perlu ditakuti. Ia optimis, media yang tidak dapat memenuhi nilai informatif akan ditinggalkan oleh publik.
Hal ini sepertinya agak sulit terjadi dengan kondisi budaya massa yang sudah terbentuk atau dibentuk oleh media itu sendiri, dimana pada akhirnya informasi yang menjadi ikon dari Budaya Massa yang terbentuk adalah isi berita yang sangat jauh dari kesan informatif.
Media massa dan Hegemoni
Dalam pandangan mazhab kritis, terutama dalam studi-studi yang dikembangkan oleh Centre for Contemporary Cultural studies, Birmingham University, media massa selalu dirasakan sebagai alat yang “powerfull” dan ada ideologi dominan di dalamnya.
Hal ini yang disebut oleh para penggiat Cultural studies sebagai hegemoni media. Teori hegemoni ini dicetuskan oleh Gramsci yang merujuk pada kekuasaan dan praktis. Hegemoni merujuk pada upaya pelanggengan kekuasaan yang dilakukan oleh kelompok yang berkuasa.
Di sini, institusi media memberikan sebuah fungsi hegemoni yang secara terus menerus memproduksi sebuah ideologi yang kohesif (ideologi yang meresap), satu perangkat nilai-nilai common-sense dan norma norma yang memproduksi dan mengesahkan dominasi struktur sosial tertentu, yang mana kelas-kelas subordinasi berpartisipasi di dalam dominasi mereka itu.
Bahkan lebih lanjut, Gitlin mendefenisikan hegemoni sebagai “rekayasa sistematik” kepatuhan massa untuk memapankan kekuasaan kelompok yang berkuasa.
Stuart Hall berpendapat Media massa cenderung mengukuhkan ideologi dominan untuk menancapkan kuku kekuasaannya melalui hegemoni. Melalui media massa juga menyediakan frame work bagi berkembangnya budaya massa.
Melalui media massa pula kelompok dominan terus-menerus menggerogoti, melemahkan dan meniadakan potensi tanding dari pihak-pihak yang dikuasainya.
Sedangkan menurut Mc. Luhan, seorang pengkritik media, mengatakan bahwa media massa bukan hanya sebagai media pengirim pesan tapi juga mempengaruhi nilai-nilai budaya dan membuat stereotip mengenai gender, ras dan etnik, memiliki kontribusi terhadap pengalaman komunikasi dan bisa saja memonopoli dunia pemikiran seseorang.
Maka dari itu selama media masih dikuasai oleh ideologi dominan, maka mereka akan menggambarkan kelompok oposisi sebagai kaum marginal. bagi Hall dan koleganya, interpretasi teks media selalu muncul di dalam suatu pertarungan dari kontrol ideologis.
Ronald Lembo dan Kenneth Tucker menggambarkan proses tersebut sebagai “arena kompetisi di mana individu atau kelompok mengekspresikan kepentingan yang berlawanan".
Apalagi jika hal tersebut sudah menyangkut bisnis, bahwa saat ini urgensi penciptaan standar kode etik bisnis media semakin besar, ketika kecenderungan konglomerasi media di tanah air semakin besar pula. Media Nusantara Citra (MNC) kini sudah memiliki RCTI, Global TV dan MNC TV.
Grup Indosiar, kini mendirikan teve lokal baru, ElShinta TV. Republika sudah dicaplok grup Mahaka Media dan kini berkolaborasi dengan JakTV.
Kompas Gramedia dan Jawa Pos Grup, yang berkuasa atas jaringan Persda dan Jawa Pos News Network di seantero nusantara. Kemudian TransCorp, yang memiliki Trans 7 dan Trans TV, dan belakangan mengakuisisi media online terbesar di Indonesia, Detik[dot]com.
Dan jangan lupa ada Media Grup dengan Media Indonesia dan MetroTV-nya. Jika tak hati-hati, raja-raja media ini bisa dengan mudah memanfaatkan jaringan medianya untuk kepentingan komersial dan pribadi mereka. Apalagi dengan keberadaan pemilik-pemilik media tersebut yang memang sangat dalam pada kehidupan, sistem dan struktur Politik di Indonesia.
Kasus Timika Pos misalnya, sebuah koran lokal yang terbit di Papua, mungkin satu contoh yang baik ditiru. Sejak mengambil alihnya dari Grup Persda -anak perusahaan Kompas Gramedia- pemilik baru media ini, Bupati Mimika Clemen Tinal, berusaha dengan segala cara memaksa redaksi Timika Pos membela kepentingan politik dan ekonominya di kabupaten kaya mineral itu.
Tak tahan dengan tindakan pemiliknya, belasan awak redaksi Timika Pos mogok kerja dan menerbitkan edisi khusus pada 6 Maret silam. Mereka menuntut pemodal menghormati independensi ruang redaksi Timika Pos dan berhenti mencampuradukkan kepentingan pribadi sang Bupati dengan kepentingan publik yang berusaha dilayani media massa.
Aksi itu cukup efektif. Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Timika Pos yang dikenal sebagai kaki tangan si pemilik media di ruang redaksi, diberhentikan.
“Komisaris perusahaan berjanji pemimpin umum dan pemimpin redaksi akan diambil dari awak redaksi sendiri,” kata Tjahjono E.P, salah seorang jurnalis Timika Pos yang juga anggota AJI persiapan Timika. Terjadi proliferasi dan konsolidasi majalah.
Proliferasi dan konsolidasi tidak jarang menghasilkan apa yang disebut dengan konglomerasi media.
Konglomerasi media terjadi ketika ada proses akumulasi dan konsolidasi bagian yang berbeda dari sekian industri media yang berbeda.
Dari uraian kerangka teori di atas maka tampak jelaslah apabila media massa akan senantiasa menjadi ajang Hegemoni bagi kelompok yang berkuasa artinya masyarakat patuh pada pada kehendak penguasa dan mereka secara tidak sadar berpartisipasi dalam rangka kepatuhan tersebut.
Independensi Media Dalam Pemberitaan
Disadari atau tidak, sebagian besar masyarakat di Indonesia masih menjadikan media sebagai salah satu jembatan informasi tentang berbagai hal yang terjadi dalam masyarakat, baik yang sedang menjadi perhatian maupun yang luput dari perhatian mereka.
Kenyataan menunjukkan, keterlibatan media dalam membentuk suatu opini publik adalah sebuah kekuatan tersendiri yang dimilikinya dan itu sangat berpengaruh dalam tatanan kehidupan di masyarakat.
Namun, seiring dengan kebebasan pers yang didengungkan dalam reformasi 1998 silam, membuat sebagian media kebablasan menyikapi eforia kebebasan tersebut. Independensi dan kode etik kadang telah tertutupi oleh orientasi bisnis dan keuntungan, sehingga saat ini ¨dapur¨ media telah dimasuki pengaruh kekuasaan, finansial dan kepentingan politik.
Media sangat memberi andil dan peran penting dalam memberikan informasi terhadap masyarakat dan kecenderungan ini kadang membuat media dalam menyajikan informasinya cenderung membuka peluang untuk terjadinya dramatisasi, manipulasi, spekulasi ataupun justru berusaha untuk tidak menyingkap kebenaran sesuai fakta sesungguhnya.
Olehnya, segelintir masyarakat berusaha memanfaatkan media untuk suatu tujuan sesuai kepentingannya, hingga kemudian media menjadi sangat sulit memisahkan antara independensi dan keuntungan bisnis, dan terkadang dua kepentingan tersebut membuat media terperosok ke dalam penyajian informasi yang tidak berimbang dan cenderung berpihak pada golongan tertentu.
Sesuai dengan pengertiannya, independensi diartikan sebagai kemandirian, dalam artian melepaskan diri dari berbagai kepentingan, mengungkapkan fakta dengan sesungguhnya dan tidak ada bentuk intervensi dari pihak tertentu dalam penyajian informasi.
Sehingga dalam membangun suatu independensi, media harus menyadari bahwa loyalitas utama adalah kepada masyarakat, dan intisari jurnalisme adalah verifikasi data yang akurat, menghindari terjadi benturan kepentingan yang berpotensi kepada pembohongan publik.
Oleh karenanya, sangat diharapkan agar seorang wartawan dalam menjalankan profesinya, harus dibarengi sikap kejujuran dalam komitmen, informasi haruslah tersaji dalam konteks kebenaran, mengetahui urutan sumber berita, transparansi dalam informasi, dan verifikasi berita secara aktual sebelum menyajikannya ke masyarakat. Bila hal tersebut dapat diwujudkan, maka media telah melakukan independensi dalam penyampaian informasi.
Saat ini, ancaman independensi media sangat beragam, namun menurut penulis, yang menjadi ancaman serius antara lain:
- Kekuasaan tidak sepenuhnya dapat di kontrol oleh media sehingga seringkali berbagai kasus penyimpangan yang terjadi hanya dapat diketahui bila ada di antara mereka (dalam lingkup kekuasaan) yang membeberkan kepada media.
- Adanya konglomerasi atau kepemilikan media yang bersentuhan dengan penguasa, sehingga informasi yang disajikan hanya berdampak pada keuntungan pihak media dan yang bersentuhan langsung dengannya.
- Kewenangan redaksi dalam mempublikasikan berita yang diperoleh dari wartawan kadang menimbulkan munculnya intervensi kepada pihak redaksi oleh orang-orang tertentu yang menganggap pemberitaan tersebut menyudutkan diri atau lingkup sosialnya.
- Masih maraknya tindak kekerasan dan pengerahan massa oleh kelompok tertentu,sehingga kalangan wartawan masih khawatir akan keselamatan dirinya dalam peliputan.
- Terjalinnya hubungan emosional antara wartawan dengan sumber berita, baik hubunganpertemanan, kekeluargaan, suku, maupun profesi sehingga bila ada pemberitaan yangmenyudutkan sumber tersebut berusaha untuk segera di tutup tutupi.
- Masih maraknya budaya amplop dan telepon, utamanya bagi golongan masyarakat yangmapan dari segi finansial, sehingga mampu mengunci akses pemberitaan.
- Upah wartawan yang tidak sebanding dengan resiko pekerjaan, hingga kadangnarasumber melakukan penyuapan kepada mereka.
- Adanya wartawan yang kurang profesional, baik dari segi penyajian berita ataupunpengolahan kata, sehingga masyarakat tidak memahami alur informasi yang diberikan dan bisa menimbulkan adanya kesalahan persepsi dan penafsiran.
- Masih ditemukannya oknum wartawan yang menganggap profesi wartawan sebagai ladang mencari nafkah, sehingga kadang dalam peliputan berita sering melakukan "penjualan" berita kepada narasumber.
- Adanya sikap masa bodoh wartawan tentang kebenaran dan sumber berita (pokoknya yang penting ada berita) menyebabkan seringnya muncul sistem Cloning atau copy-paste berita oleh sesama wartawan.
Menyajikan informasi sesuai fakta sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa melihat latar belakang sumber berita.
Manajemen media haruslah memisahkan antara redaksi pemberitaan dan unsur bisnis, sehingga menghindari adanya intervensi pemberitaan karena faktor bisnis dan tidak kalah pentingnya adalah media harus pula memperhatikan kesejahteraan wartawan, sehingga idealisme mereka tidak di kotori oleh kepentingan tertentu.
Jika ini telah di lakukan, maka kekuatan media dapat menjadi sebuah kekuatan besar yang sangat disegani oleh semua pihak, dan masyarakat akan semakin menaruh kepercayaan penuh pada keberadaan sajian informasi media. Ekonomi dan Media Massa Modern
Ekonomi dipahami sebagai ilmu atau kajian yang menelaah kekuatan atau kemampuan yang mealokasikan sumber untuk memenuhi kebutuhan yang dipersaingkan.
Dalam perkembangan media massa, yang turut juga dipengaruhi oleh masalah produksi dan distribusi massal. Ada beberapa tipe masyarakat ekonomi yang membentuk perkembangan media massa, yaitu:
- Masyarakat pertanian di mana produksi dan distribusi ditandai dengan dinamika produksi dan distribusi yang bersifat lokal dan kedaerahan.
- Masyarakat industri yang ditandai dengan standarisasi dan pengolahan produksi dan distribusi massal.
- Masyarakat informasi yang ditandai internasionalisasi dan komersialisasi informasi yang ada dalam masyarakat.
Pada dasarnya media massa mengikuti model ekonomi industrial yang ditandai dengan akselerasi banyaknya media dan hasil-hasilnya untuk mendapatkan biaya yang murah untuk produksinya.
Ketika produksi semakin besar diharapkan juga perkembangan pembeli dan cakupan daerah yang dapat membelinya. Dalam perkembangan selanjutnya, media massa juga tidak dapat dipisahkan dengan hukum persaingan karena industri media massa yang didirikan tidak lagi sebagai pemain tunggal.
Persaingan tidak dilihat sebagai hal yang negatif tapi harus dipahami sebagai hal yang membangun baik dari segi produksi dan distribusi media massa itu sendiri. Dalam iklim ekonomi, tidak menutup kemungkinan terjadinya monopoli. Atmosfer monopoli ini terjadi bisa terjadi karena sistem persaingan yang keras sehingga diperlukan pemain ekonomi yang kuat. Monopoli media bisa berbentuk dalam beberapa ragam:
- Duopoli, sebuah sistem ekonomi yang juga bisa berlaku dalam media ketika hanya terdapat dua pemain utama yang menguasai dan mendominasi 50% pasar.
- Oligopoli, sebuah sistem ekonomi yang juga bisa berlaku dalam industri media ketika terdapat beberapa industri yang menguasai dan mendominasi 30 % pasar.
- Monopoli, sebuah sistem ekonomi yang memperlihatkan satu pemain industri yang mendominasi dan menguasai hampir 90% pasar
Tapi yang jelas dari sekian motif ekonomi yang muncul, yang paling pokok adalah motif keuntungan. Faktor keuntungan adalah faktor yang mengoperasionalisasikan industri media sampai ke organisasi-organisasinya.
Dalam sebuah industri, termasuk di dalamnya industri media massa, faktor keuntungan adalah faktor penting. Faktor keuntungan ini yang sering bertabrakan dengan masalah kepentingan publik yang juga diemban oleh media massa. Untuk “menggenjot” keuntungan ini, media massa mempunyai banyak strategi dari hanya pemotongan pegawai sampai pemanfaatan iklan secara besar-besaran pada setiap produk media massa yang dihasilkan.
Tapi apakah semua media massa harus mencari keuntungan? Ternyata tidak semua, ada beberapa pelaku media (PBS, misalnya) yang tetap mengandalkan subsidi publik untuk kelangsungan hidupnya.
Kepentingan Modal atas Regulasi Media
Pada awal pembahasan revisi UU Penyiaran, fokus keberatan banyak pihak banyak tertuju pada soal peran dominan negara yang dikhawatirkan kembali lewat kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Sejumlah peran yang dibawakan oleh KPI, sebagaimana disusun dalam draft UU Penyiaran versi DPR, mendapat banyak kritik dari berbagai kelompok, misalnya soal pemberian ijin penyiaran, otoritas untuk mencabut ijin penyiaran, posisi sebagai pembina dan pengontrol isi siaran.
Penolakan atas masalah kepemilikan silang baru mencuat ketika draft ini beredar di masyarakat dan segera saja berbagai kelompok ad hoc dibentuk dan merespon pembatasan yang direncanakan dalam UU yang akan datang tersebut.
Sebagai reaksi, kemudian sejumlah kelompok industriawan penyiaran seperti ATVSI, dan Komteve menyiapkan draft RUU tandingan yang membela kepentingan televisi swasta. Mereka menginginkan bahwa televisi swasta menjadi independen dan tidak lagi dicampuri oleh intervensi pemerintah.
Kelompok-kelompok yang mengritik RUU Penyiaran versi DPR juga menggunakan argumentasi soal “kebebasan pers”, “pengkhianatan terhadap reformasi”, dan “sinergi dalam industri media” sebagai alasan mereka untuk menolak pelarangan kepemilikan silang dalam industri media.
Sumber argumentasi tentang sinergi dalam industri media, rupanya berujung pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh World Association of Newspaper (WAN) meeting di Brazil tahun 2000.
Namun tak banyak kelompok mencoba mengejar lebih jauh argumentasi tersebut. Implikasi RUU Penyiaran ini terhadap para pekerja industri media, belum banyak dikemukakan, yang lebih banyak muncul adalah argumentasi yang dikeluarkan oleh para pemilik media.
Disini menjadi penting untuk mengamati secara cermat, siapa bicara apa, karena bagaimanapun juga posisi struktural (dalam hal kepemilikan modal; antara pemilik modal dan kelompok pekerja) membedakan kepentingan yang dibawakannya.
Apakah betul jika kepentingan pemilik media yang diakomodir, dengan sendirinya mengakomodir kepentingan para pekerja media? Ilustrasi tentang hal ini menjadi sangat jelas dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh SCTV terhadap Surya Paloh, pemilik Grup Media Indonesia, dengan Djoko Susilo, anggota DPR dari Komisi I, ketika Metro TV meluncurkan siaran pertamanya.
Dilema regulasi media di Indonesia terletak pada bentuk kasar yang dilakukan oleh Negara dalam mengontrol isi, kepemilikan dan mati hidupnya media, telah membuat banyak kalangan terlena dan trauma dengan besarnya kekuasaan negara, namun lupa bahwa kekuasaan modal memiliki kekuatan yang tak kalah dashyat, bahkan mungkin lebih dashyat daripada kekuasaan negara itu sendiri.
Kekuasaan modal bisa berkolaborasi dengan jenis kekuasaan macam pun dan jenis kapitalis apapun.
Menentang intervensi negara dalam industri media adalah salah satu hal, namun memberikan fungsi baru kepada negara (dalam hal menjadi regulatory body) adalah hal yang lain lagi. Dan pada titik inilah juga persoalannya luput dibahas dalam perdebatan RUU Penyiaran itu.
Ada tendensi yang sangat besar untuk se-ekstrim mungkin menentang fungsi apapun dari negara, bahkan jika mungkin direduksi ke titik nol sekalipun. Padahal masalahnya bukan cuma soal intervensi negara dalam industri media, tapi juga mentransformasi peran baru dari negara, dari yang pengatur segalanya, menjadi pengatur untuk kepentingan publik.
Kira-kira semacam peran yang dilakukan di negeri-negeri yang menganut system welfare state. Dan yang patut dilihat secara cermat adalah kecerdikan kelompok pemodal untuk menutupi kepentingan ekspansi modal mereka dengan jargon-jargon yang seolah-olah membela kebebasan pers, membela akses masyarakat terhadap informasi, hingga membela proses reformasi dan demokratisasi.
Disinilah dilema terbesar yang akan dihadapi oleh negara-negara yang mengalami situasi transisional, dimana kekuatan negara mulai terpecah atau bahkan diganti secara keseluruhan, namun di sisi lain kekuatan modal lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang ada, dan bahkan dengan sangat mudah beradaptasi dengan kekuasaan baru.
Dan praktis kekuatan modal tidak memiliki jaringan birokrasi yang seluas birokrasi negara, yang memudahkan kekuatan modal untuk mengontrolnya, apakah mereka akan bisa berjalan bersama dengan pemerintahan baru, ataukah mereka akan mencari tempat lain dimana kekuatan negara bisa bekerjasama dengannya.
Dalam situasi globalisasi, hal ini menjadi sangat dimungkinkan, dimana pergerakan kapital menjadi sangat mudah dan khusus dalam situasi seperti di Indonesia, ada kelompok pengusaha yang diuntungkan dengan situasi yang berubah dan ada pula pengusaha yang tidak diuntungkan.
Industri media termasuk salah satu yang mengalami keberuntungan dengan perubahan situasi ini karena dengan deregulasi dan liberalisasi yang terjadi dalam sector media, maka mereka segera menjadi kapitalis-kapitalis baru atau semakin memperkuat posisi mereka untuk tumbuh di Indonesia.
Di satu sisi memang, masalah monopoli informasi adalah hal yang masih banyak diperdebatkan, namun memiliki 100 buah penerbitan di 30 buah propinsi di Indonesia, bukanlah pertanda yang sehat untuk perkembangan industri media yang lebih beragam dan membuka pilihan yang lebih baca kepada konsumen.
Kelompok media besar pun cenderung bungkam atas isu ini, dan perdebatan soal kepemilikan silang ini nyaris luput dari perhatian, dan energi banyak dihabiskan untuk membahas situasi dilematis dari KPI.
Persoalan modal memang merupakan persoalan yang cukup pelik, karena hal ini cenderung diabaikan dalam berbagai literatur soal demokrasi. Problem demokrasi lebih banyak berurusan dengan kondisi represif negara terhadap warganya dan berbagai usaha untuk mendobrak dominasi tersebut. Namun apa yang terjadi dengan perkembangan modal dan bagaimana ia pun menelikung berbagai problem lain, jarang diberikan perhatian secara proporsional.
Kasus yang ditunjukkan di atas barulah bicara dalam tataran kepentingan modal ‘lokal’ dan belum lagi bicara dalam konteks modal ‘global’ yang masuk dalam industri media di Indonesia, dengan segala sifatnya yang tidak mengenal batas wilayah, capital yang sangat mobile, dan juga capital yang bisa mempengaruhi factor-faktor kehidupan dalam masyarakat, seperti ekonomi, politik, budaya dan lain-lain.
Masih banyak hal yang perlu dipelajari untuk mengenal karakter modal dan bagaimana dilematisnya posisi soal modal dalam industri media ini, terutama dalam situasi masyarakat post-authoritarian (atau kondisi yang akan kembali menjadi authoritarian?).
Setidaknya kasus ini hendak memberikan suatu ilustrasi bahwa problem kebebasan pers, bukan semata-mata bagaimana ia bisa bernegosiasi dengan kekuasaan negara yang represif, tapi juga ia harus berhadapan dengan kepentingan pemilik modal, karena bagaimana pun juga industri media lain dengan industri-industri lainnya, berurusan dengan soal pembentukan citra yang dimediasi lewat media-media yang ada.
Lalu implikasinya kepada para pekerja media, pada kehidupan masyarakat luas dan lain-lain, masih harus diselidiki lebih jauh. Sejak ekonomi informasi berkembang pada era 1960-an ditandai dengan ledakan informasi yang kemudian menumbuhsuburkan bisnis media, tak dapat dipungkiri, bahwa kuku kapitalisme pun telah menancap di dunia permediaan.
Media tidak lagi hanya menjadi mesin ideologi informasi yang memiliki spektrum tanggung jawab sosial dan partisipasi politis dalam mengritisi kebijakan-kebijakan penguasa, tetapi media pun telah menjadi mesin pencetak uang dan modal, tak ubahnya seperti lembaga-lembaga bisnis yang lain. Ideologi bisnis bergerak koheren dengan ideologi politik, sosial-budaya, agama dan ideologi kepentingan lainnya.
Bahkan, dalam tidak sedikit kasus, kepentingan bisnis menjadi yang terdepan. Terlebih dengan makin ketatnya persaingan bisnis antarmedia.
Persaingan ini pula yang menjadikan kepemilikan media tidak lagi dalam satu warna, sehingga menarik untuk ditelaah. Yang awalnya pesaing, dengan logika bisnis dapat berubah seketika menjadi mitra bahkan saudara seatap.
Demikian pula sebaliknya, yang tadinya saudara atau mitra strategis, dapat serta-merta berubah menjadi pesaing utama. Sukses-gagal, mati-tumbuh ataupun sakit-segar menjadi dinamika tersendiri dalam fenomena perkembangan bisnis dan kepemilikan media.
Hal ini pula yang terjadi di Indonesia. Ketika keran bisnis media dibuka sekaligus memecah kebekuan ‘monopoli siaran’ TVRI yang merupakan milik pemerintah pada awal 1990-an, kepemilikan media masih berupa kepemilikan tunggal. Namun, pada era 2000-an, peta kepemilikan media di Indonesia bergerak ke arah konglomerasi.
Trans TV dengan Trans Corp-nya mengakuisisi TV7 dan mengubahnya menjadi Trans7. Demikian pula konglomerasi MNC yang dikomandani RCTI, berhasil ‘menyatukan’ TPI dan Global TV dalam satu atap. Terakhir adalah akuisisi La Tivi sebelum berubah menjadi TVOne oleh sebuah kolaborasi bisnis yang salah pemegang sahamnya adalah kelompok Bakrie yang juga pemilik AnTeve.
Sementara AnTeve pun telah menjalin kemitraan bisnis dengan kelompok StarTV milik raja media Rupert Murdoch di bawah payung News Corp. Yang menarik, konglomerasi kepemilikan media di Indonesia lebih didorong oleh persaingan dalam perebutan iklan serta efisiensi produksi, dan terakhir sekarang adalah kepentingan pemiliknya dalam kontestasi politik (ini yang berbahaya).
Sedangkan konglomerasi global lebih bermotifkan kapitalisasi informasi, sehingga penekanan pada “bisnis informasi” menjadi sangat dominan. Media tidak hanya sebagai penayang, tetapi juga pemasok informasi atau isi tayangan ke media-media lain.
Dengan demikian, iklan tidak menjadi “panglima” bisnis, tetapi informasi-lah yang menjadi panglimanya. Mereka menjual hak siar di mana-mana dan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Iklan menyusul.
Bisnis media di Indonesia belum mencapai taraf menjadikan informasi sebagai core business. Indonesia masih lebih banyak mengandalkan “kue” iklan yang pada tahun 2008 diprediksi Rp 60 triliun (14).
Uniknya, meskipun salah satu alasan konglomerasi media yang ditandai dengan aksi akuisisi dan merger adalah perebutan iklan, namun pengiklan tidak serta-merta menjadikan kepemilikan tersebut sebagai dasar dalam penentuan strategi pemasangan iklan. Faktor rating acara masih tetap menjadi pertimbangan utama.
Sehingga, kepemilikan media yang didasarkan atas perebutan iklan patut dipertanyakan. Teknologi komunikasi mungkin menjadi hal yang sangat menarik bagi para pengusaha untuk berinvestasi.
Buktinya, banyak sekali terjadi konglomerasi atas media. Konglomerasi – satu perusahaan besar menaungi beberapa media sekaligus. Contoh yang sangat terlihat di Indonesia tentang adanya konglomerasi yaitu MNC dan Trans Corp.
Kedua perusahaan tersebut menguasai beberapa media sekaligus, misalnya MNC memiliki Global TV, RCTI dan MNC TV media juga tidak bisa mengelak mengenai isi yang akan cenderung sama, walaupun hanya pada saat ada event tertentu saja (monopoli isi media).
Dengan penyamaan atas isi media ini, orang-orang tidak akan memiliki kebebasan untuk memilih content media yang mereka inginkan. Hal ini juga akan sangat berkaitan erat dengan tumbuhnya semangat kapitalisme dalam industri media.
Industri media yang dibangun dengan semangat kapitalisme tentu akan menghasilkan pesan atau produk media yang berorientasi pada bertambahnya modal.
Bukti untuk produk media berorientasi modal adalah banyaknya iklan komersial dan besarnya pengaruh iklan dalam penentuan suatu program.
Selain itu isi media sekarangpun menjadi kurang berkualitas dan hanya mementingkan keuntungan. Industri media sangat erat kaitannya dengan tumbuhnya semangat kapitalisme.
Munculnya konglomerasi media, satu perusahaan besar menaungi beberapa media sekaligus seperti misalnya MNC dan Trans Corp, dianggap sebagai aktivitas pemusatan modal dalam industri media.
Pertanyaan yang seringkali diajukan adalah apakah industri media memberi andil besar menyebarkan virus kapitalisme dalam urat kehidupan masyarakat.
Atau justru semangat kapitalisme yang mengawali tumbuh suburnya industri media raksasa, di samping faktor regulasi.
Tidak mudah menjawab pertanyaan tersebut, karena fenomena tersebut terjadi bukan di ruang hampa, bukan hanya permasalahan antara media dan kapitalisme saja. Tetapi juga melibatkan komponen lain dalam kehidupan sosial.
Sehingga yang terjadi bukanlah sebuah proses linear melainkan kesalingterkaitan antarkomponen dalam sistem sosial yang jika divisualisasikan mungkin akan menjadi bentuk coretan semrawut.
Industri media yang dibangun dengan semangat kapitalisme tentu akan menghasilkan pesan atau produk media yang berorientasi pada bertambahnya modal.
Bukti untuk produk media berorientasi modal adalah banyaknya iklan komersial dan besarnya pengaruh iklan dalam penentuan suatu program.
Mungkin sebagian besar isi media tidak secara eksplisit menunjukkan keberpihakannya. Tetapi secara halus pesan-pesan kapitalisme yang menuntun pada perilaku konsumtif masyarakat disisipkan melalui tayangan sinetron, acara gosip, kuis berhadiah, polling sms dan lain sebagainya.
Selain pesan/produk media yang pro-kapitalisme, sebaliknya ada juga pesan media anti-kapitalisme yang nantinya akan diresepsi oleh audiens. Pesan anti-kapitalisme bisa berbentuk kritik atas pesan/produk media kapitalisme atau praktek kapitalisme oleh media.
Dalam kaitannya dengan hubungan dalam institusi media, konglomerasi media sedikit banyak mempengaruhi kondisi, cara dan hasil kerja para pekerja media. Misalnya saja, satu pesan/produk media, yang seharusnya untuk ditayangkan oleh satu stasiun TV saja, bisa ditayangkan juga di stasiun TV lain yang masih dalam satu korporasi.
Ibaratnya seorang pekerja bekerja untuk dua atau lebih perusahaan dengan standar gaji satu perusahaan. Kondisi ini jelas mempengaruhi cara kerja pekerja media yaitu keseragaman pesan, timbulnya persaingan tidak sehat antarpekerja bahkan berpotensi menjadi perbudakan pegawai media.
Pesan-pesan media tersebut, baik pro maupun anti-kapitalisme, pasti membawa dampak pada audiens meski dengan tingkatan yang berbeda-beda.
Ada yang sebatas pada pengetahuan tentang pengertian dan praktek kapitalisme, ada yang sudah mengambil sikap terhadap kapitalisme dengan mendukung atau menolak, ada pula yang menjadi pelaku dalam bisnis kapitalisme, bahkan ada yang sudah terjerat masuk dalam lingkaran kapitalisme tapi tidak menyadarinya.
Golongan yang terakhir adalah pihak yang sering kita sebut sebagai korban kapitalisme. Biasanya berasal dari golongan menengah ke bawah dengan ciri pola konsumsi tinggi.
Perbedaan pengaruh tersebut wajar terjadi karena tiap individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami dan mengkonstruksi pesan.
Mungkin saja untuk audiens mendapatkan informasi yang berlainan dengan pesan kapitalisme misalnya norma agama, sosial, adat budaya yang mengajarkan tentang hidup sederhana, hemat, kesetiakawanan.(Oleh Reiza Patters, jurnalis warga)
Daftar Pustaka
1. Griffin EM (2005) “A First look at Communication Theory” Six Edition Mc Graw Hill
2. Heryanto Ariel (2000) Perlawanan dalam kepatuhan Esai-esai budaya Dr. Ariel Heryanto Mizan Bandung.
3. Hidayat, Dedy. N., 2000, Pers dalam Revolusi Mei: Runtuhnya Sebuah Hegemoni, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
4. Irawanto Budi (1999). Film ideology dan Militer: Hegemoni Militer dalam sinema Indonesia. Media Pressindo : Yogyakarta
5. Latif Yudi dan Idi Subandy Ibrahim (eds) (1996) Bahasa dan Kekuasaan: Politik wacana panggung Orde Baru .Mizan Bandung
6. Littlejohn, Stephen W (2005) Theories of Human Communication. Wadworth Publishing Company : Belmont
7. Marpaung Tegar (2007) Pers Indonesia Pasca reformasi (antara kebebasan , tantangan dan harapan ) Makalah persentasi MK. Dinamika Kekuatan politik Indonesia
8. Seminar Nasional dengan tajuk Media Massa di Era Cyberspace: Tinjauan Kritis Terhadap Obyektivitas Media Saat Ini, Jakarta, 13 Oktober 2009, Badan Penerbitan Pers Mahasiswa (BPPM) EQUILIBRIUM, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM
9. Toriq Hadad, Seminar Nasional dengan tajuk Media Massa di Era Cyberspace: Tinjauan Kritis Terhadap Obyektivitas Media Saat Ini, Jakarta, 13 Oktober 2009, Badan Penerbitan Pers Mahasiswa (BPPM) EQUILIBRIUM, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM
10.Djadjat Sudrajat, Seminar Nasional dengan tajuk Media Massa di Era Cyberspace: Tinjauan Kritis Terhadap Obyektivitas Media Saat Ini, Jakarta, 13 Oktober 2009, Badan Penerbitan Pers Mahasiswa (BPPM) EQUILIBRIUM, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM
11.Wahyu Dhyatmika & Herawatmo, Aji
12.Feintuck, Mike, 1998, Media Regulation, Public Interest, and The Law, London:Edinburg University Press
13.Gibbons, Thomas, 1998, Regulating Media, London:Sweet & Maxwell 14.Bisnis Indonesia: 11 April 2008.
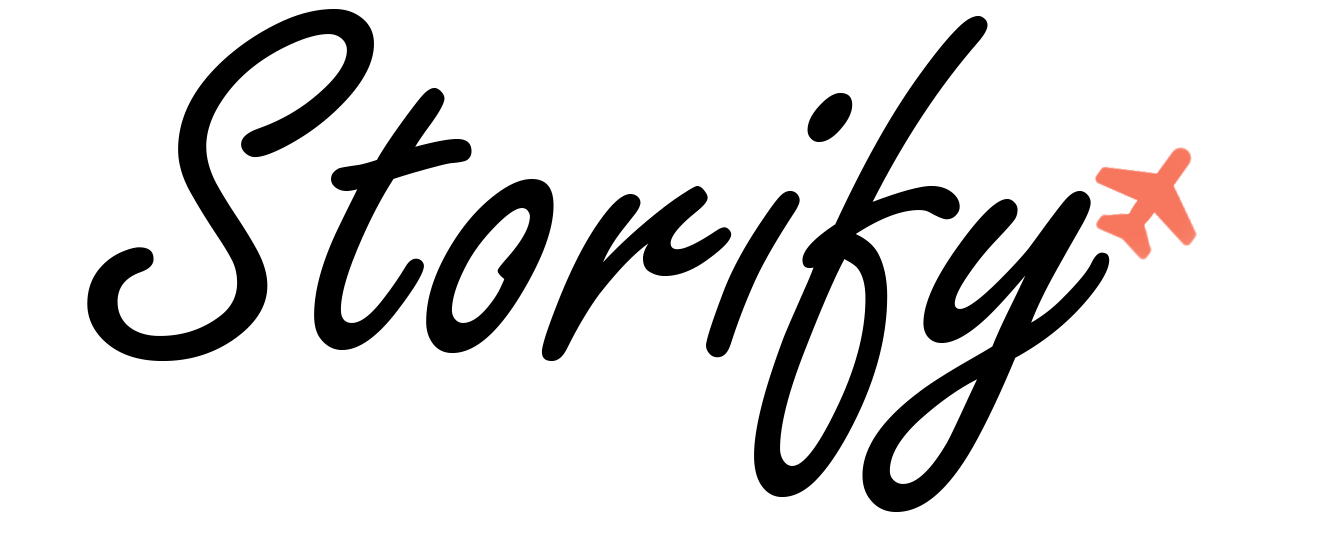









COMMENTS